Relasi Indonesia-Myanmar
Catatan-catatan ringkas tentang implementasi kerja sama perdagangan kedua negara itu sebenarnya merupakan bagian dari sejarah panjang relasi antara Indonesia dan Myanmar. Dalam catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, relasi kedua negara telah terjalin sejak era tahun 1945, terutama pasca Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Dukungan Burma terhadap eksistensi kemerdekaan Indonesia sangatlah kuat. Bahkan, sebelum negara itu merdeka–4 Januari 1948–otoritas setempat telah memberi izin kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka kantor perwakilan di Yangon–kala itu disebut dengan Rangoon. Izin itu diberikan mengiringi kedatangan perwakilan Indonesia, Marjunani ke Rangoon pada 1947.
Catatan sejarah itu tertoreh dalam sebuah laporan tahunan KBRI Yangon yang salinannya terpasang di dinding sebuah lorong di kompleks KBRI. Dalam salah satu paragraf laporan tahunan itu disebutkan, Pemerintah Burma, walaupun belum dapat mengakui kita dengan resmi karena ikatan internasional, telah menunjukkan lebih dari rasa simpati saja. Sedemikian pemerintah dan sedemikian pula rakyatnya. Tanda pertama dari sumbangan itu adalah pemberian tempat kediaman dan kantor kepada saudara Marjunani di suatu flat gedung Kementerian Luar Negeri Burma yang sekarang.
Tentu saja, dukungan itu memberi energi tambahan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia yang kala itu masih berupaya keras mempertahankan kemerdekaan, terutama dari ancaman agresi militer Belanda. Pasca kemerdekaan Myanmar, Rumah Indonesia di Yangon itu kemudian ditingkatkan statusnya menjadi KBRI pada April 1950. Saat itu—dalam catatan KBRI Yangon—Presiden Soekarno memuji Myanmar sebagai ”Kawan dalam memperjuangkan dan mencapai kemerdekaan sejati”.
Pada masa-masa awal perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, Myanmar—yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris—terus menunjukkan dukungannya. Mereka tidak hanya mengecam agresi militer Belanda, tetapi juga memberi izin Dakota RI-001 Seulawah—pesawat pertama yang dibeli oleh rakyat Indonesia—mendarat di Bandara Mingaladon, Yangon, pada 26 Januari 1949. Kejadian bersejarah itu menjadi bagian dari tonggak kelahiran maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia.
Memasuki era tahun 1950-an ketika dunia tertarik dalam dua kutub AS dan Uni Soviet, Indonesia—diwakili Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo bersama mitra di kawasan, termasuk Myanmar yang diwakili Perdana Menteri U Nu memelopori lahirnya gerakan non-blok. Gerakan yang juga dimotori oleh PM Jawaharlal Nehru dari India, PM Mohammad Ali Bogra dari Banglades, dan PM Sir John Kotelawala dari Sri Lanka itu melahirkan negara-negara baru di kawasan.
Hingga saat ini dukungan politik Myanmar terhadap Indonesia tidak pernah berubah. Myanmar adalah salah satu negara pertama yang mengeluarkan pernyataan—baik melalui KBRI maupun forum resmi, seperti ASEAN Ministrial Meeting (AMM), ASEAN Regional Forum, dan pertemuan lain–menyokong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pernyataan itu didengungkan terutama saat Indonesia tengah dirundung gejolak internal saat menghadapi kampanye yang disponsori Gerakan Aceh Merdeka atau gerakan separatis dari Organisasi Papua Merdeka. Pemerintah Myanmar menegaskan, tidak akan membiarkan wilayah mereka digunakan sebagai pangkalan kegiatan yang memusuhi NKRI. Mereka pun turut mengawasi kemungkinan penyelundupan senjata ke wilayah Indonesia.
Tidak mengherankan jika Pemerintah Indonesia pun terus kuat menjaga relasi itu. Keanggotaan Myanmar di dalam asosiasi regional ASEAN, tak lepas dari campur tangan Indonesia. Indonesialah yang menjadi sponsor utama Myanmar. Dalam lanskap regional, keterlibatan Myanmar di dalam asosiasi itu memperkuat dan memperkokoh kehadiran ASEAN di kawasan.
Asosiasi itu mampu menjadi soko guru stabilitas di kawasan dan menjadikannya salah satu tempat paling menarik untuk berinvestasi. Hingga saat ini, kekuatan ekonomi dunia, seperti AS, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok serta Australia terus menjalin kerja sama ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan dengan ASEAN.
Dalam relasi bilateral, hubungan antara Indonesia dan Myanmar terus diperkokoh. Para pemimpin kedua negara saling bertandang. Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat pernah mengunjungi Myanmar. Sebaliknya, pemimpin Myanmar, seperti Jenderal Senior Than Swe dan Perdana Menteri Thein Sein, pun tercatat pernah mengunjungi Indonesia.
Dikabarkan, Penasihat Negara Myanmar—yang juga tokoh demokrasi negara itu—Aung San Suu Kyi juga berkeinginan berkunjung ke Indonesia. Adapun Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus mengikuti dari dekat perkembangan Myanmar, termasuk dalam isu-isu sosial-politik, seperti terjadi di Negara Bagian Rakhine.
Sebagai salah satu motor penggerak demokrasi di kawasan, Indonesia—sebagai mitra sejajar—terus membuka diri bagi Myanmar. Saat negara itu perlahan-lahan membuka diri dan membangun demokrasi, Indonesia hadir membantu dengan tidak memosisikan diri sebagai guru atau pengajar.
Implementasi dari sikap itu tampak jelas dan membuahkan hasil positif. Sekjen Konsorsium Aceh Baru Juanda Djamal dalam Kompas, 5 Januari 2012, menulis, pasca badai Nargis menghantam negara itu pada Mei 2008, Myanmar memasuki peradaban yang lebih terbuka. Mereka menyadari bahwa kekuasaan militer tak dapat menempatkan diri mereka untuk bersanding dan bersaing secara global. Atas dasar itulah Myanmar pelan-pelan membangun paradigma baru pemerintahan yang demokratis. Lebih menarik lagi, pasca Nargis, Pemerintah Myanmar menghendaki ASEAN berperan dalam penanganan tersebut. Indonesia menjadi pilihan mereka.
Juanda melanjutkan, dalam transisi demokrasi di Myanmar, Pemerintah Indonesia memiliki modal besar untuk terlibat, yang dimulai sejak rekonstruksi bencana badai Nargis di mana beberapa ahli rekonstruksi Indonesia terlibat. Indonesia juga mendukung Pemilu 2010 dan terakhir mendukung kepentingan politik luar negeri Myanmar sebagai Ketua ASEAN 2014.
Menurut dia, Indonesia memiliki kapital yang sangat tinggi untuk bisa menancapkan pengaruh politik luar negerinya, misalnya pembelajaran dari reformasi dan demokratisasi nasional, desentralisasi, dan mekanisme otonomi khusus, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, hingga proses perdamaian dan demokrasi di Aceh.
Kala itu, Juanda juga melontarkan kritik, modal sosial itu—yang selayaknya menjadi senjata diplomasi di kawasan itu— kurang dioptimalkan Jakarta. Ia menyebutkan, Myanmar sebagai satu isu strategis di tingkat internasional semestinya dapat dimanfaatkan oleh Kemlu RI untuk memulai beberapa kerja sama penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara atau regional. Misalnya, kerja sama peningkatan kapasitas pemimpin politik melalui beberapa program kunjungan, pertukaran pengalaman, dan pendidikan singkat dalam bidang legislatif. Begitu pula di bidang penguatan masyarakat madani, bisnis, perdagangan, dan sebagainya.
Namun, merujuk pada sikap dan kebijakan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia atas isu Myanmar tidak semata-mata didasarkan pada aspek pemenuhan fakta dan kenyataan politik di kawasan. Sebagai tetangga dan mitra dekat di kawasan, Indonesia lebih memilih untuk memenuhi kewajiban sebagai sahabat daripada memanfaatkan kedekatan itu.
Dalam sebuah perbincangan, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib mengatakan, dalam menyikapi persoalan yang dihadapi negara mitra, Indonesia tidak pernah mau menunjuk-nunjukkan jari atau membuat kecaman. Sebaliknya keprihatinan Indonesia justru ditunjukkan dengan membangun komunikasi intensif dan hadir bersama untuk menemukan solusi komprehensif.
Sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Kleib dan berkali-kali diulang oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, pendekatan yang inklusif dan komunikatif terkait berbagai persoalan di Myanmar justru membuahkan hasil optimal. Saat Myanmar kembali digoyang isu konflik komunal dan bersenjata—yang kemudian berkembang menjadi isu diskriminasi rasial—Indonesia kembali tidak memosisikan sebagai guru atau memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan politik nasional ataupun regional.
Sejak lima tahun lalu, saat konflik komunal yang berakar pada persoalan ekonomi dan kemiskinan meletus di Sittwe, Indonesia selalu hadir bagi semua pihak dan komunitas di Myanmar. Pendekatan inklusif yang antara lain ditunjukkan dengan membangun empat sekolah, masing-masing dua untuk komunitas Muddhis dan Muslim, kembali diterapkan saat ini pasca terjadinya serangan di tiga pos polisi di Maungdaw, 9 Oktober 2016. Bantuan-bantuan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik diberikan kepada setiap komunitas.
Di depan Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar Dr Win Myat Aye di Sittwe, Menlu Retno mengatakan, pendekatan inklusif yang dilakukan Indonesia diarahkan untuk membangun perdamaian antarkomunitas. Melalui perdamaian itulah stabilitas dapat diwujudkan dan kesejahteraan bersama dapat diraih.
Sikap inklusif dan tidak menggurui itu pula yang di lapangan justru membuka banyak pintu. Tak hanya bantuan dari Pemerintah Indonesia saja yang mendapat akses, tetapi juga media, dan aneka lembaga swadaya dan ormas nasional yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia memperoleh kesempatan untuk turut membantu. Tawaran Indonesia untuk meningkatkan akses warga pada pelayanan kesehatan dan pendidikan mendapat sambutan baik. Bahkan, tawaran Indonesia untuk membangun pasar perdamaian sebagai bentuk rekayasa sosial untuk mempertemukan aneka komunitas di Rakhine juga antusias disambut.
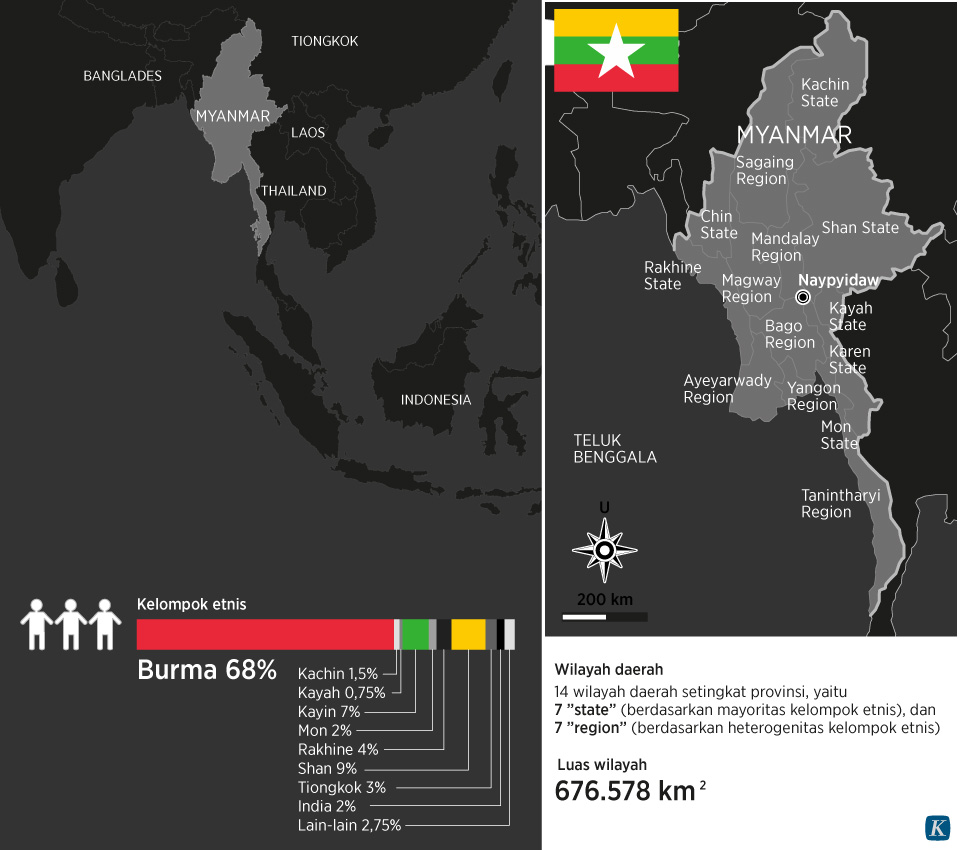






 }})





