Adagium musuh dari musuhku adalah kawanku berlaku di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia dalam upaya menghancurkan Indonesia. Meski Belanda sudah mengakui keberadaan Republik Indonesia melalui pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, unsur-unsur Belanda pro-penjajahan terus mencari kesempatan untuk mengganggu dan menyabotase keberlangsungan Republik Indonesia hasil Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.
Salah satu upaya menghancurkan Republik Indonesia yang dilakukan elemen-elemen subversi Belanda terjadi di tahun 1950-an bekerja sama dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan SM Kartosoewirjo. Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 menelikung Republik Indonesia yang sedang memasuki tahap akhir perjuangan diplomasi melawan Belanda.
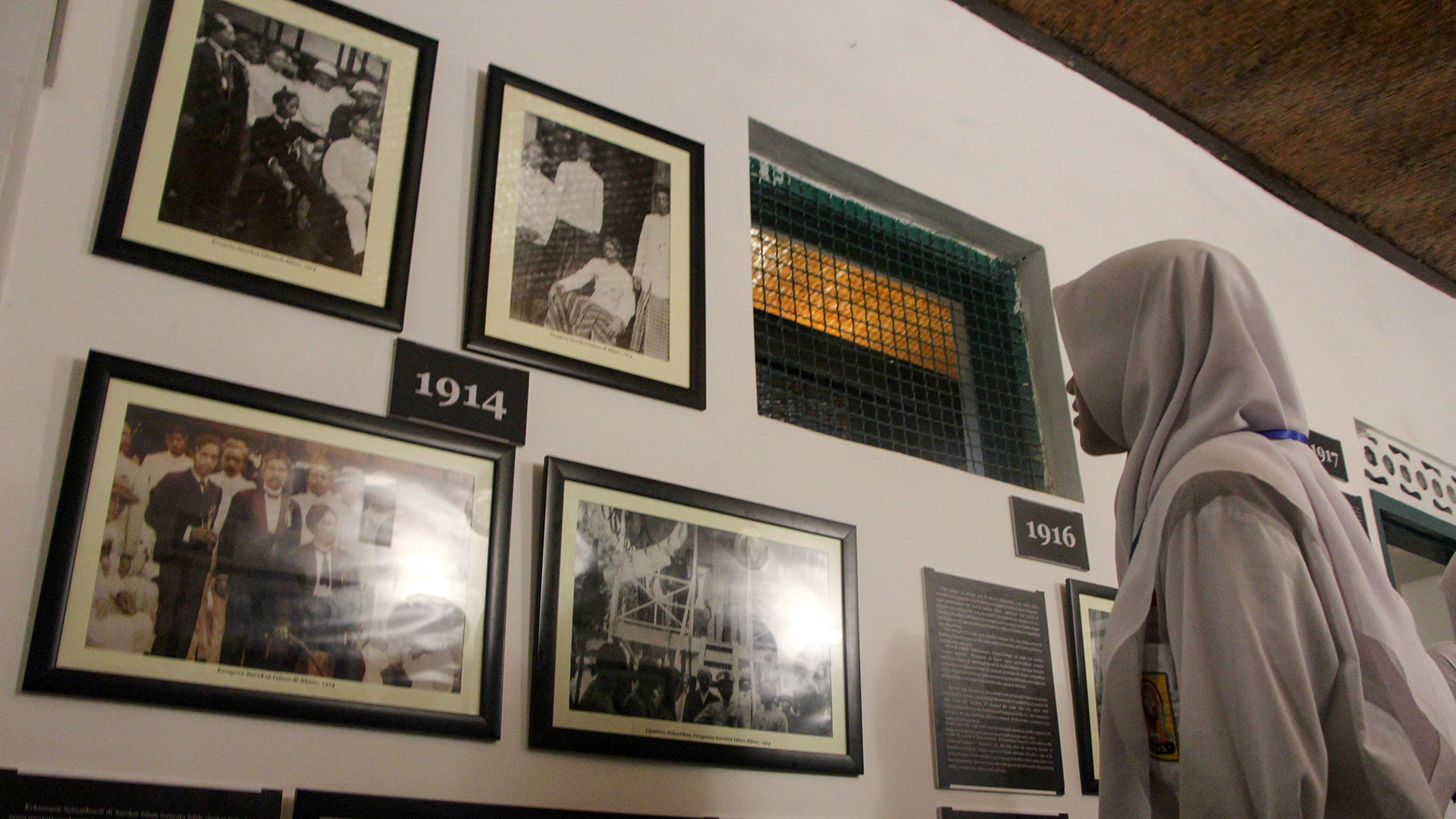
Sejarawan Hendi Jo menceritakan, bahkan salah satu orang Belanda tersebut menjadi orang kepercayaan SM Kartosoewirjo, yakni CH Van Kleef—mantan anak buah Westerling—yang berperang bagi DI/TII hingga menemui ajalnya di Cisaat, dekat Sukabumi, Jawa Barat, pada awal 1960-an.
”Yang menarik adalah ketika Raymond Westerling memimpin pemberontakan APRA di Kota Bandung, tanggal 23 Januari 1950, pada hari yang sama DI/TII melancarkan serangan di Kota Tasikmalaya dan Kota Garut yang merupakan basis kekuatan mereka. Sebelum pemberontakan tersebut, disebutkan ada kesepakatan antara kubu Westerling dan Kartosoewirjo. Hal itu mengemuka dalam persidangan dari keterangan seorang anggota DI, yakni Haris bin Suhaemi, yang menceritakan 10 hari sebelum pemberontakan APRA menyerang Kota Bandung, pemimpin APRA Westerling, pemimpin DI/TII Kartosoewirjo, dan Kepala Negara Pasundan, yakni Wiranatakusumah, bertemu secara rahasia di Hotel Preanger, Bandung,” Hendi Jo menerangkan.
Kalau pemberontakan APRA yang dibarengi serangan DI/TII berhasil di Jawa Barat, disepakati, secara de facto Darul Islam akan berkuasa di Jawa Barat.
Hendi Jo menambahkan, CH Van Kleef juga menyurati Westerling agar kembali ke Jawa di tahun 1952 untuk berjuang bersama melawan Republik Indonesia. Van Kleef yang mantan opsir polisi di Bogor itu juga menjelaskan, pihak Negara Islam Indonesia (NII) sudah berkomunikasi dengan Amerika Serikat. Pihak Amerika, menurut Hendi Jo, sempat mengirim utusan, tetapi berhasil ditangkap aparat Indonesia.

Silang sengkarut hubungan DI/TII dengan Belanda membingungkan, mengingat antara Agresi II Belanda pada Desember 1948 hingga tahun 1949, terjadi saling serang DI/TII melawan Belanda di Jawa Barat. Kemudian terjadi pertarungan DI/TII-Belanda-TNI atau Pasukan Teritorium Siliwangi.
Ketika pemberontakan APRA berhasil dipatahkan TNI, ujar Hendi Jo, sisa-sisa serdadu APRA kabur ke arah Ciranjang dan barat Bandung ke Cianjur dan Sukabumi. Sebagian dari mereka berhasil bergabung dengan pasukan pemberontak DI/TII.
Para serdadu DI/TII di sekitar Bogor juga mendapat pasokan senjata dari Piet Colson, ajudan Kapten Raymond Westerling. Lokasi di Bogor itu diyakini di sebelah barat Bogor di daerah Dramaga yang merupakan bekas landhuiskeluarga Van Motman, tuan tanah superkaya yang menguasai tanah perkebunan puluhan ribu hektar di tahun 1800-an. Sebagian pasukan DI/TII yang kemudian ditangkap hidup atau mati didapati mengenakan seragam militer dengan motif kamuflase—cammo—sama persis dengan model militer Belanda.
Wilayah Dramaga itu menjadi pusat operasi NIGO (Nederlansch Indie Guerilla Organisatie atau Organisasi Gerilya Hindia Belanda), White Eagles atau Witte Arend, dan Nederlands zal Herrijzen atau Belanda akan bangkit kembali, semboyan yang banyak digunakan saat Belanda diduduki Nazi Jerman.
Sejarawan Firman Lubis dalam buku Jakarta 1950-an Kenangan Semasa Remaja menceritakan, di tahun 1953, Indonesia digegerkan dengan persidangan terhadap Jungschlager dan Schmidt.
Mereka adalah bagian dari jaringan intelijen Kapten Raymond ”Turk” Westerling dan mantan anggota NEFIS (Netherlands Forces Intelligence Service) yang aktif semasa Perang Dunia II. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 1957 mengeluarkan laporan tentang gerakan subversif tersebut dengan judul Subversive Activities in Indonesia: The Jungschlager and Schmidt Affair.