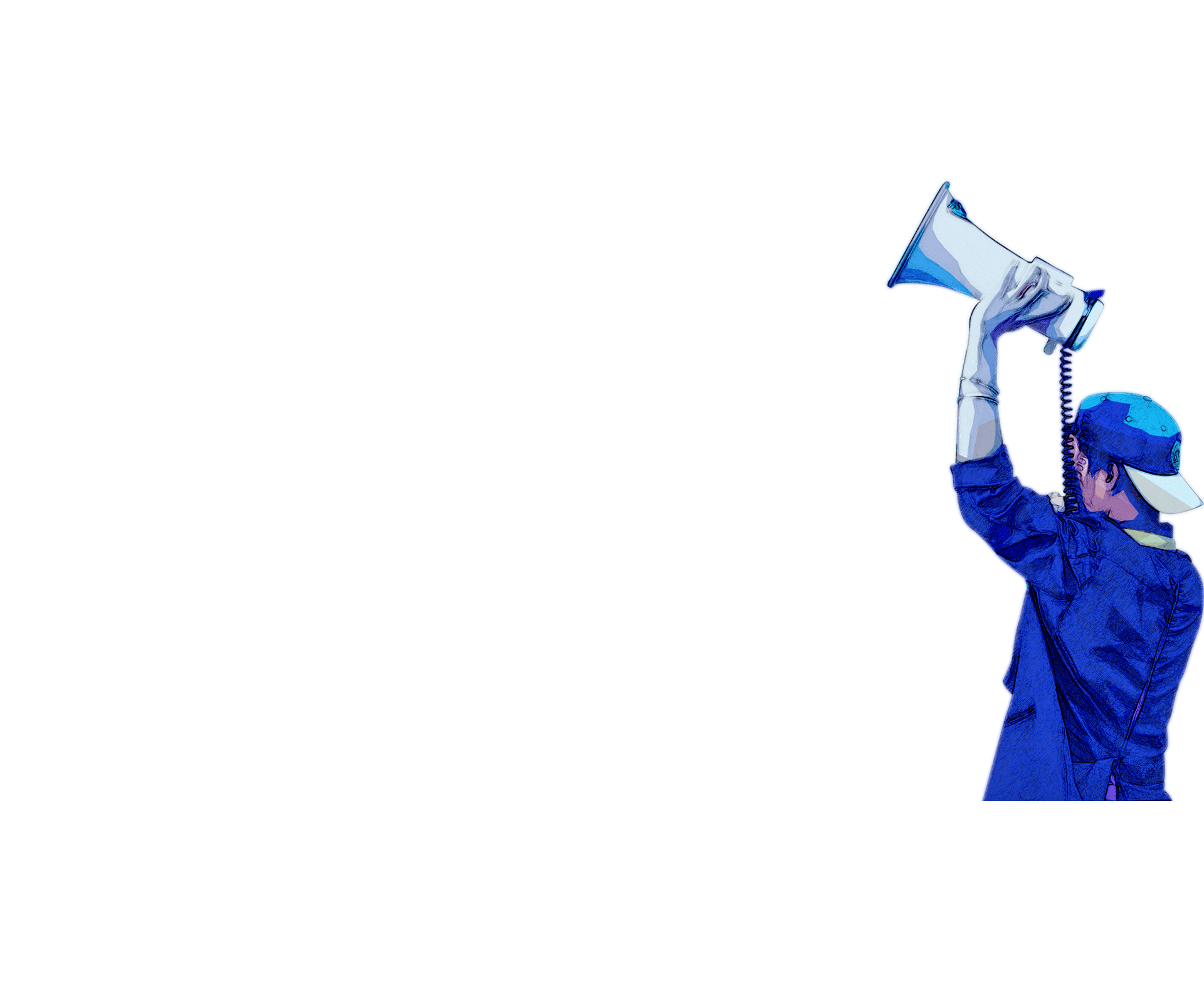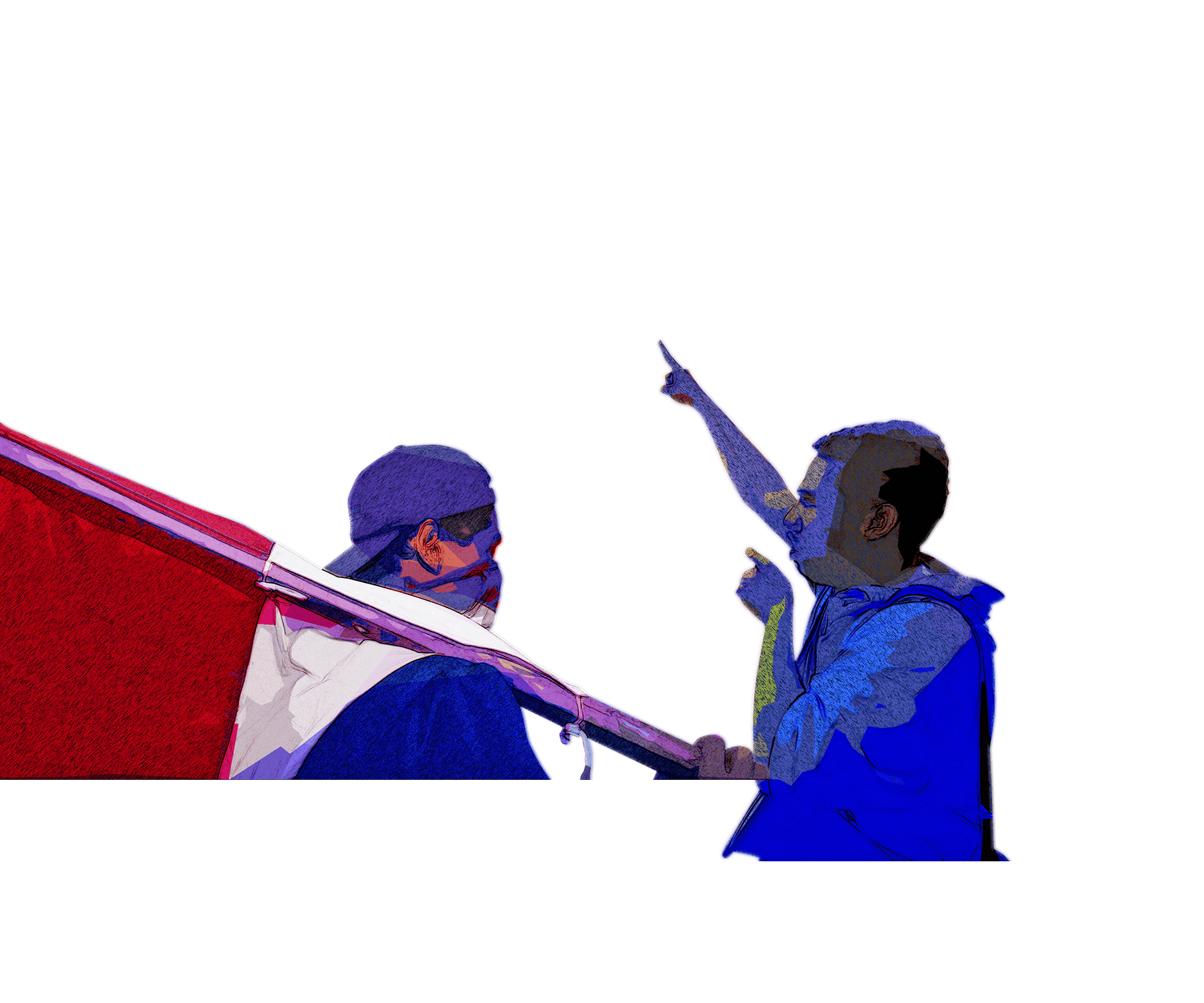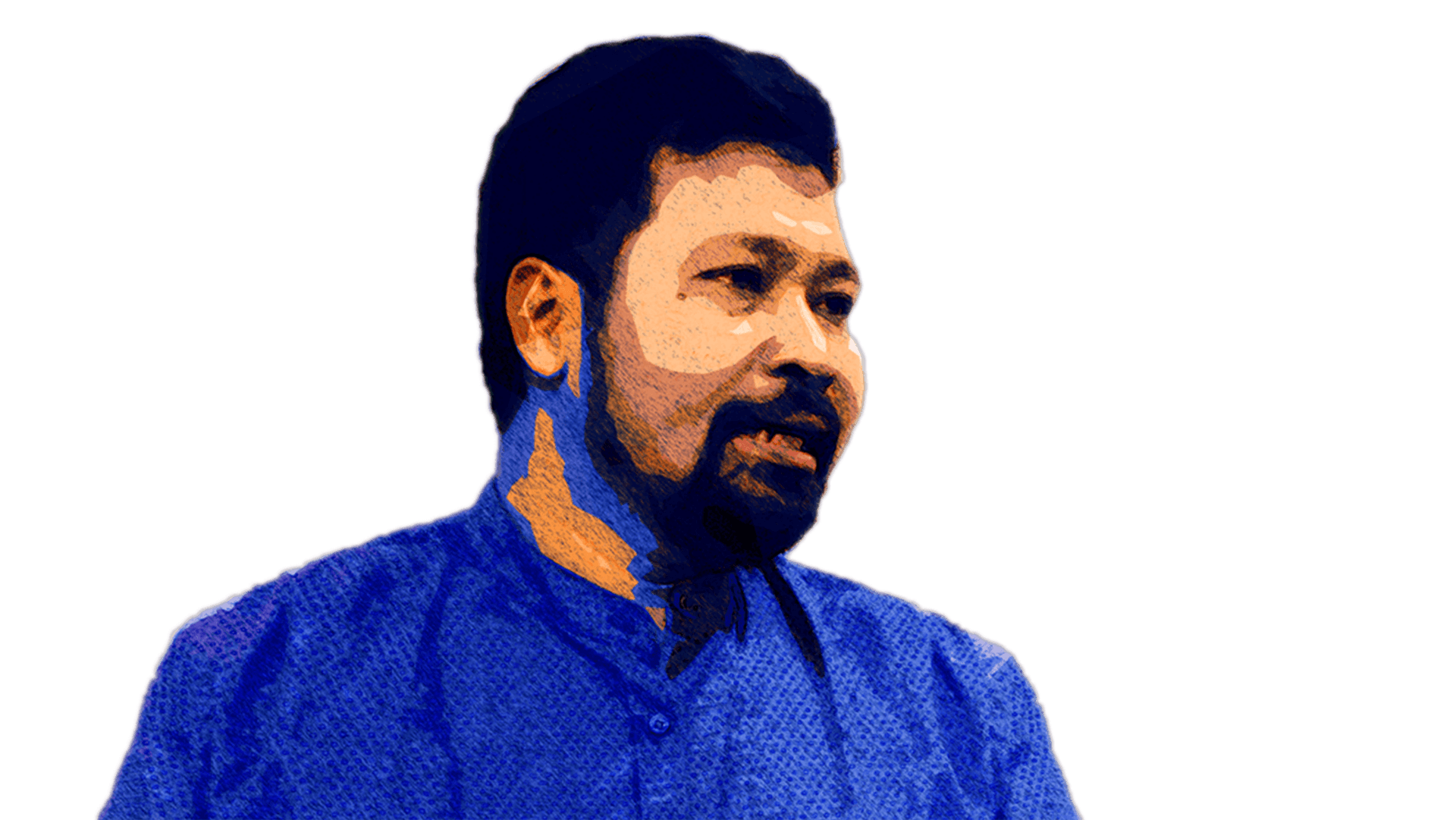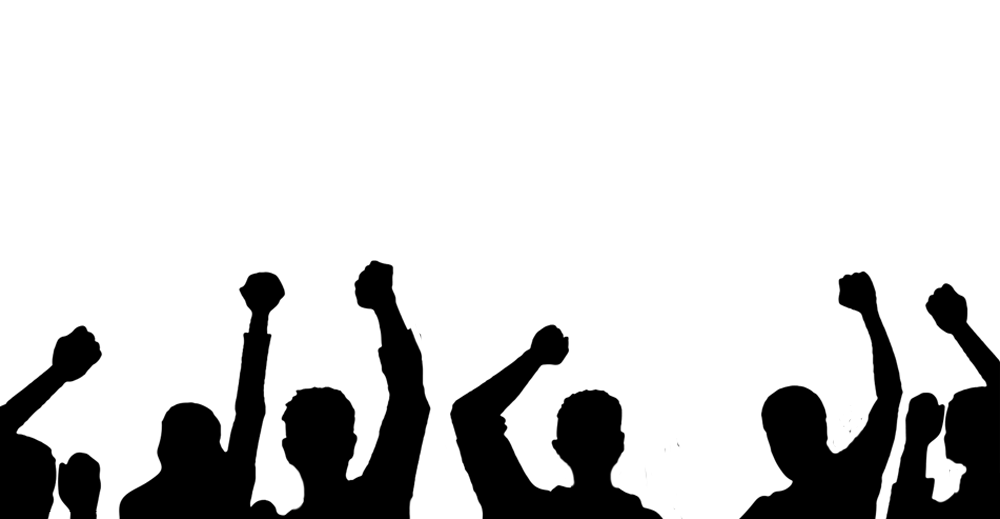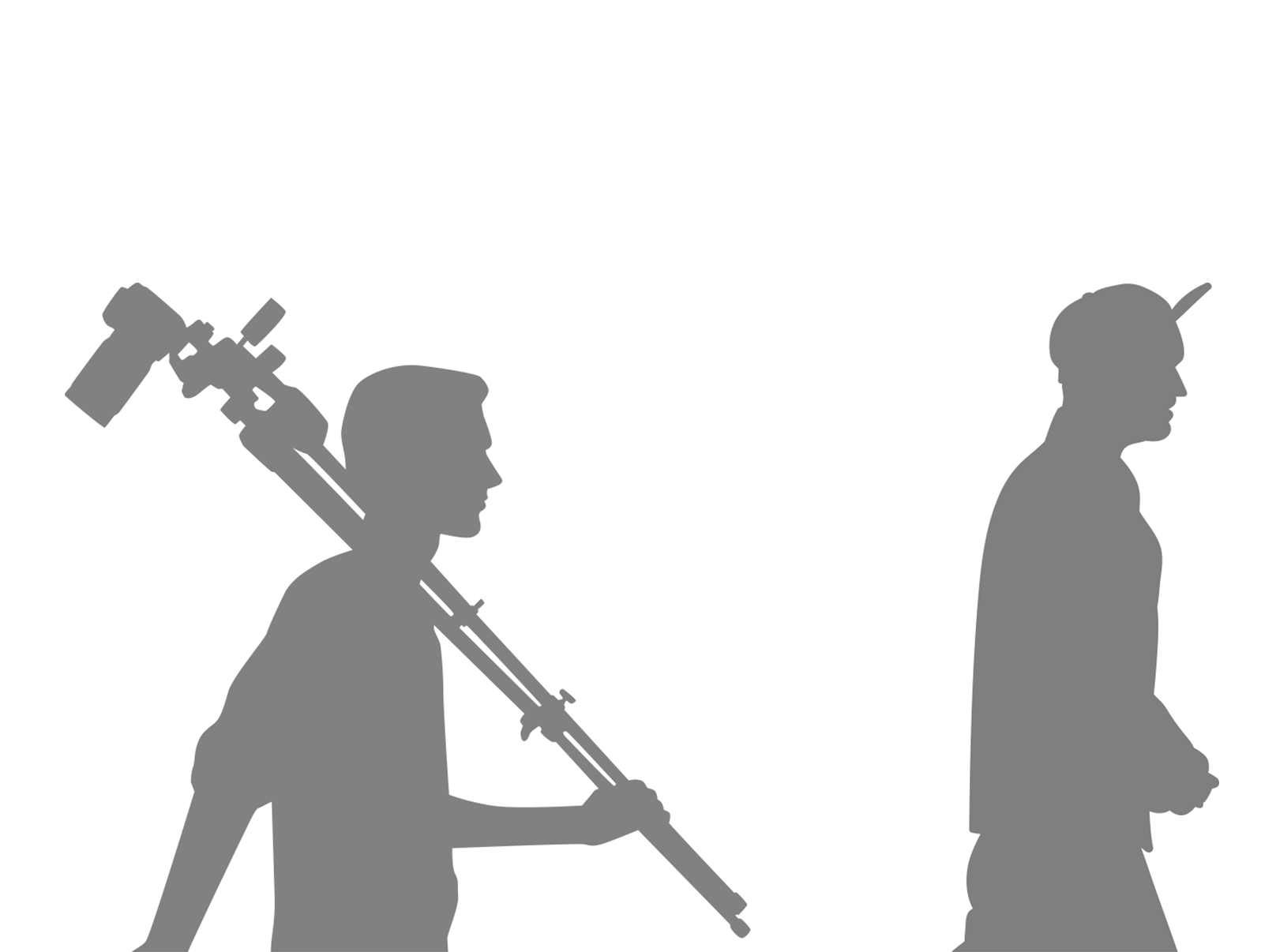Dalam kajian Joseph Daves berjudul, ”Colonel Suwarto and The Indonesian Socialist Party” disebutkan, kunjungan Kolonel Suwarto—kelak pensiun dengan pangkat letnan jenderal—ke Rand Corporation, Amerika Serikat, tahun 1962, menghasilkan konsep Dwifungsi. Konsep ini kemudian diterapkan rezim Orba di bawah Soeharto setelah dibahas dalam Seminar Angkatan Darat Tahun 1965 dan 1966.
Pada era Orba, jangankan bicara ganti presiden Indonesia, mengkritik ketua RT, RW, bupati, dan wali kota pun dapat bermasalah. Terlebih lagi, pemerintah masih represif, mulai dari membungkam aksi mahasiswa hingga penghilangan nyawa manusia tanpa pertanggungjawaban.
Suatu hari, Kompas pernah bertanya kepada Komandan Korem Suryakancana, Bogor, menjelang Pemilu 1992 terkait prospek suksesi kepemimpinan nasional. Danrem yang kemudian pensiun sebagai seorang letnan jenderal itu menuding-nuding Kompas dan menyatakan hal itu tidak pantas untuk ditanyakan.
Ikrar Nusa Bhakti dan kawan-kawan dalam buku Tentara yang Gelisah menyatakan, dwifungsi ABRI sebagai ”sumber bencana nasional”. Krisis yang memicu Reformasi Mei 1998 juga dipicu terlalu besarnya kekuasaan eksekutif di Orba.
Besarnya kekuasaan eksekutif ini juga sudah terjadi pada era Orde Lama (Orla). Namun, berbeda dengan masa Orla, pada masa Orba, ABRI selalu mendukung pemerintah.
Tentu saja, ada berbagai aksi untuk mencoba mengoreksi Orba dari waktu ke waktu. Pada dekade 1970-an, misalnya, ada beberapa aksi, seperti Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada 28 Mei 1971, Peristiwa Malari 15 Januari 1974, dan aksi demo di depan Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada 28 Oktober 1977.
Namun, upaya-upaya itu gagal. Tiga tahun setelah kegagalan Malari, mahasiswa semakin bosan dengan segala macam kebobrokan. Padahal, kedua orde itu sama-sama punya kredo, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Kekecewaan mahasiswa memang beralasan. Periode awal pemerintahan Soeharto diwarnai megakorupsi Pertamina. Nilai korupsi Pertamina membuat semua orang menganga. Nilai korupsi Rp 90 miliar uang negara saat nilai tukar 1 dollar AS masih Rp 400. Pertamina pun nyaris bangkrut seketika dengan utang 10 miliar dollar AS.
Gelombang aksi pun terus terjadi. Di Surabaya, peringatan Hari Pahlawan tahun 1977 disemarakkan oleh mahasiswa. Di Jakarta, 6.000 mahasiswa berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari Rawamangun (Kampus IKIP Jakarta) menuju Salemba (Kampus Universitas Indonesia), membentangkan spanduk bertuliskan ”Padamu Pahlawan Kami Mengadu”.
Semua aksi ini dikawal tentara. Beberapa batalyon tempur sudah ditempatkan mengitari kampus-kampus Surabaya. Sepanjang jalan ditutup, mahasiswa tak boleh merapat kepada rakyat.
Ketika itu dicanangkan Ikrar Mahasiswa 1977, yakni ”Kembali pada Pancasila dan UUD ’45, meminta pertanggungjawaban presiden, dan bersumpah setia bersama rakyat menegakkan kebenaran dan keadilan”.
Tahun berikutnya, tepatnya pada momen peringatan 12 tahun Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), 10 Januari 1978, kembali digelar aksi unjuk rasa. Peringatan 12 tahun Tritura itu menjadi semacam penanda akhir gerakan mahasiswa tahun 1970-an.
Ketika itu, penguasa menganggap mahasiswa sudah melampaui batas. Masa teror dan pengekangan dimulai. Beberapa media massa pun diberedel penguasa Orba, termasuk harian Kompas.

 Sepenggal Kisah Reformasi
Sepenggal Kisah Reformasi